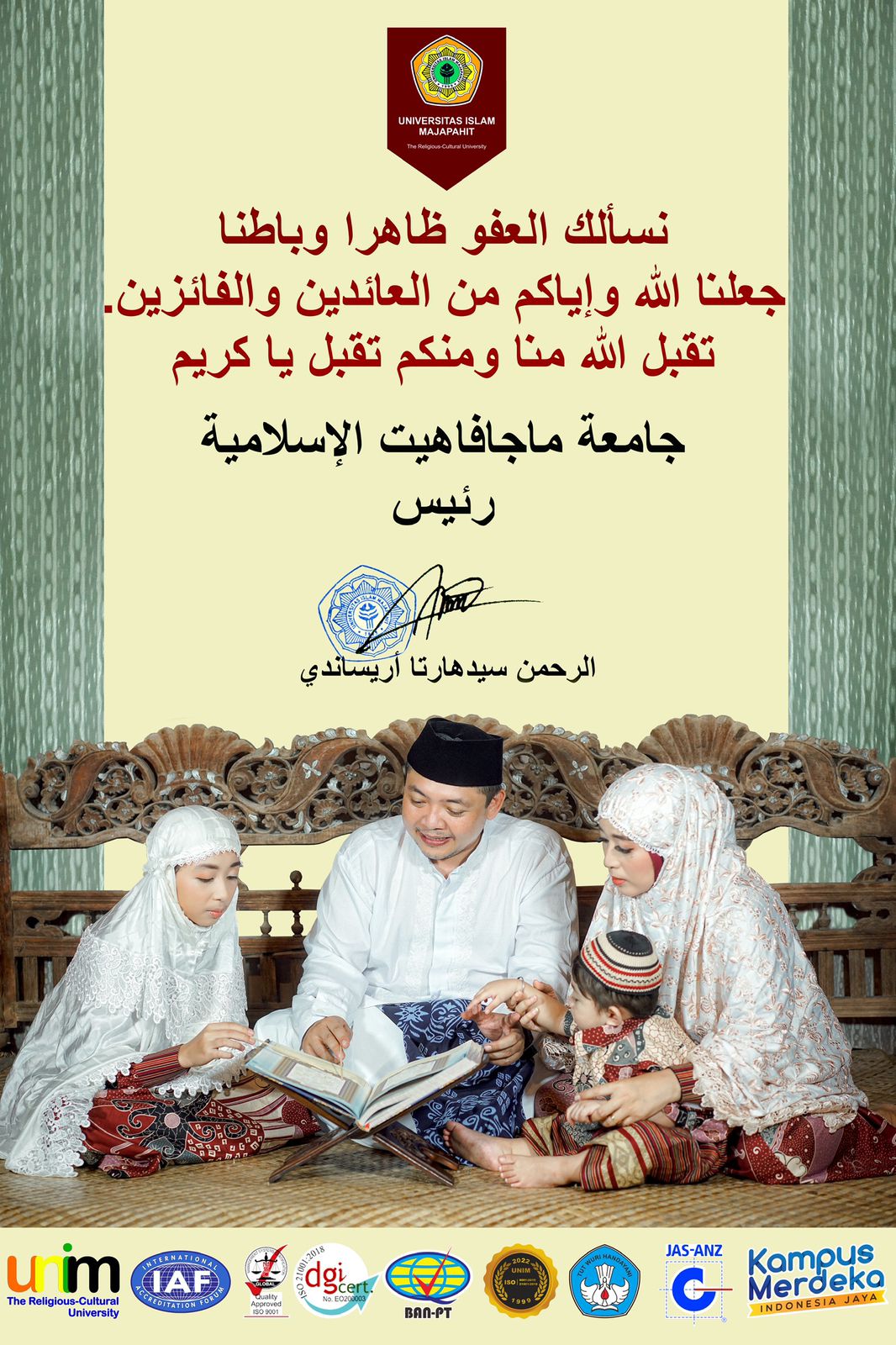Tugujatim.id – Tahun 2017 lalu, saya terlibat dalam bedah buku karya pemikir Islam Al Ghazali berjudul “Terbebas dari Kesesatan” (Al Munqid min Adh-Dhalal). Buku ini diterjemahkan oleh Ach. Khoiron Nafis, salah satu santri Pesantren Luhur Baitul Hikmah, Kepanjen, Kabupaten Malang, tempat di mana saya juga belajar.
Saat itu, saya sebagai moderator dan pembedahnya adalah Kiai Ach. Dhofir Zuhry yang sekaligus pendiri Pesantren Luhur Baitul Hikmah yang juga dikenal Pesantren Filsafat. Diskusi saat itu membuat saya sangat terkesan, baik terhadap pemikiran Al Ghazali maupun pada upaya penejemahan yang dilakukan oleh Bung Nafis, saya memanggilnya seperti itu.
Tak lama setelah itu, saya berpisah dengan Bung Nafis karena harus melanjutkan tugas di Yogyakarta. Nah, belum lama ini setelah balik ke Malang, saya silaturahmi ke pesantren tersebut. Saya menyebutnya bukan silaturahmi, tapi pulang. Saya menganggap Luhur Baitul Hikmah bukan saja tempat belajar, tapi juga rumah buat saya. Di dalamnya ada sahabat dan teman yang sudah menjadi keluarga.
Setelah tiba di halaman depan pesantren, terlihat satu bangunan lantai dua setengah jadi. Di kanan kiri bangunan itu ada potongan bambu, tumpukan batu bata, semen, dan agak jauh di depan bangunan itu ada pasir dan alat-alat bangunan lainnya. Saya melangkah mendekat dan melihat di sekitar, berjarak sekitar 15 meter di depan bangunan itu ada fondasi yang ternyata untuk musala. Memang Pesantren Luhur Baitul Hikmah sedang melakukan pembangunan yang cukup besar.
“Saat ini, kami masih fokus ke pembangunan Bung,” ujar pemuda asal Pontianak tersebut sembari mempersilakan saya duduk di lantai dua gedung tersebut.
Dia kemudian beranjak ke bagian belakang gedung. Ternyata dia membuatkan saya kopi. Kami memang sebelumnya biasa berdiskusi dan membaca ketat teks-teks filsafat sembari ngopi dan rokokan.
“Tapi, masih ada teman-teman yang sempat berdiskusi filsafat. Saya sendiri mulai fokus ke tafsir,” ujarnya sambil menghidangkan kopi ke hadapanku dan segera menyeret asbak.
Dia juga menunjukkan beberapa kitab tafsir karya Fakhruddin Ar Razi yang dia kaji belakangan ini. Ar Razi adalah mufasir besar dalam Islam yang sekaligus murid Al Ghazali yang dikagumi oleh Nafis. Dalam kesempatan tersebut, selain berbincang sejarah dan perkembangan seputar filsafat Islam kontemporer, kami juga ngobrol tentang penerjemahan teks-teks filsafat di Indonesia.
Setelah menerjemahkan Al Munqid min Adh Dhalal, Nafis memang banyak memeriksa terjemahan karya-karya Al Ghazali dalam bahasa Indonesia, salah satunya Tahafut at Falasifah (Kerancuan Para Filsuf). Menurut dia, ada beberapa terjemahan di dalamnya yang kurang pas dan membingungkan pembaca.
“Setelah kami kaji dengan mengomparasi teks asli (Arab) dengan terjemahan Indonesia, banyak yang kurang pas. Makanya, selama ini kami sulit memahaminya yang versi bahasa Indonesia,” keluhnya.

Bung Nafis memang menguasai bahasa Arab sehingga dia dengan mudah mendeteksi padanan kata atau frasa yang kurang tepat dalam terjemahan bahasa Arab. Hal itu pulalah yang mendorong pemuda yang pernah jadi lurah pesantren tersebut melakukan koreksi beberapa buku terjemahan lainnya, misalnya Falsafatuna, karya Baqir Shadr, pemikir Islam kontemporer.
“Dalam terjemahan penerbit Mizan, ada yang kurang tepat. Misalnya ada kata ‘aradh (Inggris: accident) ternyata diterjemahkan menjadi kebetulan. Padahal yang tepat adalah aksiden,” tuturnya menunjukkan beberapa persoalan terjemahan buku tersebut.
Dia mengatakan, ke depannya mereka berencana untuk menerjemahkan ke dalam dua bahasa.
“Kami berencana untuk menerjemahkan dalam dua bahasa buku itu (Falsafatuna), yaitu bahasa Indonesia yang disandingkan dengan bahasa Arabnya. Ini sekaligus untuk pembelajaran dalam menerjemah,” ungkapnya.
Saya pun langsung mendukung proyek tersebut. Karena memang penerjemahan buku yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi si penerjemah maupun pembaca. Dan pembaca dapat mengakses teks asli dari suatu penulis, sementara penerjemah bisa dapat uang atas bayaran terjemahannya.
“Menarik itu Bung,” saya mendukung.
Saya pun mendukung proyek itu karena sangat bermanfaat bagi keduanya.
“Dengan menerjemah kita dapat dua, membaca teksnya dan dapat uang kalau diterbitkan,” saya melanjutkan dukungan.
Saya pun berbagi cerita menerjemah dengan Bung Nafis. Ada empat buku terjemahan yang pernah saya lakukan dan diterbitkan, di antaranya: tiga karya Plato yaitu Meno, Apology, dan Parmenides dan satu karya Rene Descartes yaitu Meditations of First Philosophy. Empat karya itu, tiga diterbitkan Indoliterasi dan satu diterbitkan Basa-Basi.
“Cuma memang bayaran penerjemah di Indonesia tidak terlalu besar Bung, rata-rata per lembar dihargai belasan ribu,” paparku.
Diskusi siang itu terus berlanjut ke berbagai topik lainnya, termasuk ke perkembangan filsafat bahasa di Indonesia saat ini. Dan juga ada beberapa teman lainnya yang ikut nimbrung untuk turut bercerita banyak hal seputar filsafat. Namun sayang, waktu kian sempit sementara perbincangan semakin mengasyikkan.
Diskusi terjemahan dan topik-topik filsafat tidak akan pernah ada akhirnya dan akan semakin menarik. Tapi, waktu dan ruang selalu menjadi pembatas. Akhirnya, kami mengakhiri obrolan tersebut dan kami bersepakat untuk mencari waktu luang agar bisa kembali berdiskusi seputar filsafat.